Weekly outline
General
Mata kuliah ini membahas aspek geografis dari proses transmigrasi dan perkembangan permukiman, terutama dalam konteks pembangunan wilayah dan pemerataan penduduk. Fokus utama terletak pada pemahaman hubungan antara manusia, ruang, dan lingkungan dalam dinamika mobilitas penduduk serta perubahan penggunaan lahan.
Materi mencakup teori dan konsep dasar transmigrasi, sejarah kebijakan transmigrasi di Indonesia, pola dan persebaran permukiman, faktor penentu lokasi permukiman, dampak sosial-ekonomi dan lingkungan dari program transmigrasi, serta strategi perencanaan permukiman yang berkelanjutan. Mahasiswa juga akan menganalisis studi kasus dan data spasial untuk memahami keberhasilan maupun tantangan dalam implementasi program transmigrasi di berbagai wilayah.
Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:
-
Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi transmigrasi dan pola permukiman;
-
Menganalisis keterkaitan antara kebijakan transmigrasi dan pembangunan wilayah;
-
Merancang pendekatan geografis dalam perencanaan permukiman yang adil dan berkelanjutan.
-
PERTEMUAN 1: KONSEP DASAR, SEJARAH DAN TUJUAN TRANSMIGRASI DI INDONESIA
Upload tugas disini
PERTEMUAN 2: JENIS TRANSMIGRASI DAN KARAKTERISTIK TUJUAN TRANSMIGRASI
Upload tugas disini
PERTEMUAN 3: HUBUNGAN UNSUR GEOSFER TERHADAP KEBIJAKAN TRANSMIGRASI
HUBUNGAN UNSUR GEOSFER TERHADAP KEBIJAKAN TRANSMIGRASI
1. Pendahuluan
Transmigrasi merupakan program pemindahan penduduk dari daerah padat ke daerah jarang penduduk dengan tujuan pemerataan pembangunan, pengurangan kepadatan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam praktiknya, kebijakan transmigrasi sangat dipengaruhi oleh unsur geosfer, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Pemahaman hubungan ini penting agar transmigrasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan masalah baru.
2. Unsur Geosfer dan Hubungannya dengan Transmigrasi
a. Atmosfer (Iklim dan Cuaca)
Hubungan: Iklim mempengaruhi jenis tanaman yang bisa dibudidayakan transmigran, ketersediaan air hujan, serta adaptasi terhadap kondisi lingkungan.
Contoh:
Transmigrasi ke Kalimantan dan Papua harus memperhatikan curah hujan tinggi yang berpotensi banjir atau rawa, sehingga jenis tanaman pangan harus disesuaikan (padi rawa, sagu, palawija).
b. Litosfer (Tanah, Geologi, Relief)
Hubungan: Kondisi tanah dan bentuk permukaan bumi menentukan kelayakan lahan pertanian, infrastruktur, dan permukiman.
Contoh:
Lahan gambut di Kalimantan yang semula digunakan untuk transmigrasi ternyata tidak subur, sulit dikelola, sehingga menimbulkan kegagalan panen.
Sebaliknya, lahan subur di Lampung (dataran rendah dengan tanah aluvial) berhasil menunjang pertanian padi dan singkong bagi transmigran Jawa.
c. Hidrosfer (Air Permukaan dan Tanah)
Hubungan: Sumber air menentukan keberlangsungan hidup transmigran untuk minum, pertanian, dan sanitasi.
Contoh:Transmigrasi di Sumatera Barat harus dekat sungai atau membuat sumur dalam, karena keterbatasan air bersih.
Di daerah pesisir Sulawesi, diperlukan teknologi pengolahan air karena sumber air tanah cenderung payau.
d. Biosfer (Keanekaragaman Hayati)
Hubungan: Flora dan fauna di lokasi transmigrasi mempengaruhi pola mata pencaharian, peluang usaha, sekaligus potensi konflik ekologi.
Contoh:Di Papua, hutan lebat berpotensi hasil hutan non-kayu (rotan, damar, gaharu) sebagai ekonomi alternatif bagi transmigran.
Namun, perlu menjaga kelestarian hutan agar tidak terjadi deforestasi besar-besaran akibat pembukaan lahan transmigrasi.
e. Antroposfer (Kependudukan dan Sosial Budaya)
Hubungan: Unsur manusia adalah inti transmigrasi, meliputi kepadatan, budaya, kearifan lokal, hingga interaksi dengan penduduk asli.
Contoh:Transmigrasi Jawa ke Lampung berhasil membentuk masyarakat majemuk, memunculkan kampung-kampung transmigran yang kini berkembang menjadi kota baru.
Namun, di beberapa daerah (misalnya Kalimantan), perbedaan budaya antara transmigran dan penduduk lokal sempat menimbulkan konflik sosial.
3. Integrasi Unsur Geosfer dalam Kebijakan Transmigrasi
Perencanaan lokasi transmigrasi harus mempertimbangkan semua unsur geosfer agar tidak menimbulkan masalah jangka panjang.
Pendekatan spasial sangat diperlukan dalam menentukan wilayah tujuan transmigrasi (misalnya dengan SIG dan penginderaan jauh).
Kebijakan baru: sejak 2015, pemerintah lebih menekankan transmigrasi berbasis potensi wilayah (one village one product), bukan sekadar memindahkan penduduk.
4. Kesimpulan
Unsur geosfer memiliki hubungan erat dengan kebijakan transmigrasi. Iklim, tanah, air, keanekaragaman hayati, dan kondisi sosial budaya menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Kegagalan memperhitungkan salah satu unsur bisa menyebabkan transmigrasi tidak berhasil, sebaliknya pemahaman komprehensif akan mendukung keberhasilan pembangunan
Secara umum pelaksanaan transmigrasi telah menunjukkan keberhasilan dalam berbagai pembangunan. Namun, di balik keberhasilan tersebut, berbagai stigma negatif melekat pada program transmigrasi. Terkait dengan stigma negatif ini, Siswono (2003) juga mengemukakan beberapa aspek yang menyebabkan terpuruknya citra program transmigrasi yang bermuara pada penolakan di berbagai daerah. Di antaranya adalah: (a) terlalu berpihaknya kepada etnis pendatang (transmigran) dalam pemberdayaan dan pembinaan masyarakat di unit pemukiman transmigrasi (UPT) dan kurang memperhatikan penduduk sekitar. Perbedaan ini, mengakibatkan perkembangan UPT relatif lebih cepat ketimbang desa-desa sekitarnya sehingga menimbulkan kecemburuan yang berdampak sangat rentan terhadap konflik; (b) sistem pemberdayaan dan pembinaan masyarakat transmigrasi dilaksanakan dengan pendekatan sentralistik, yang mengakibatkan budaya lokal nyaris tidak berkembang, sementara budaya pendatang lebih mendominasi; proses perencanaan kawasan permukiman transmigrasi kurang dikomunikasikan dengan masyarakat sekitar. Akibatnya, masyarakat sekitar permukiman transmigrasi tidak merasa terlibat, dan karenanya tidak ikut bertanggung jawab atas keberadaannya; (d) adanya pembangunan permukiman transmigrasi yang eksklusif sehingga dirasakan kurang adanya keterkaitan secara fungsional dengan lingkungan sekitarnya; (e) adanya pemukiman transmigrasi yang tidak layak huni, layak usaha dan layak berkembang dan justru menjadi desa tertinggal.
PERTEMUAN 4: QUIS
Program transmigrasi di Indonesia telah mengubah pola permukiman dari wilayah asal (Jawa, Bali, Madura) ke daerah tujuan (Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua).
Analisislah bagaimana perubahan pola permukiman akibat transmigrasi memengaruhi struktur keruangan desa di daerah tujuan!
Soal 2
Di beberapa daerah tujuan transmigrasi muncul dinamika sosial berupa interaksi antara penduduk asli dengan transmigran, yang bisa melahirkan integrasi maupun konflik.
Analisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik sosial atau ketidakselarasan budaya di wilayah permukiman transmigrasi!
Soal 3
Sebagian besar wilayah transmigrasi menghadapi tantangan seperti degradasi lahan, aksesibilitas rendah, dan ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Berdasarkan analisis soal 1 dan 2, rumuskan strategi pembangunan permukiman berkelanjutan yang dapat mengintegrasikan kepentingan transmigran, penduduk lokal, serta kelestarian lingkungan.
PERTEMUAN 5: DAMPAK SOSIAL, EKONOMI, BUDAYA DAN LINGKUNGAN DARI PROGRAM TRANSMIGRASI
1. Pendahuluan
Program transmigrasi adalah kebijakan pemindahan penduduk dari daerah berpenduduk padat (umumnya Pulau Jawa, Bali, Madura) ke daerah berpenduduk jarang seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Tujuannya meliputi pemerataan penduduk, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan wilayah baru.
2. Dampak Sosial Transmigrasi
a. Dampak Positif
-
Pemerataan penduduk
Mengurangi tekanan penduduk di daerah asal dan mengisi ruang kosong di daerah tujuan. -
Pembentukan permukiman baru
Munculnya desa atau kota baru yang menjadi pusat aktivitas sosial dan pemerintahan. -
Akses pelayanan sosial meningkat
Transmigran mendapatkan fasilitas dasar seperti sekolah, puskesmas, jalan, dan listrik. -
Mobilitas sosial dan kualitas hidup meningkat
Banyak transmigran yang sebelumnya petani penggarap berubah menjadi pemilik lahan. -
Kerja sama sosial antar masyarakat
Interaksi antara penduduk lokal dan transmigran menciptakan bentuk sosial baru, seperti kelompok tani dan organisasi masyarakat.
b. Dampak Negatif
-
Konflik sosial
Timbul akibat perebutan lahan, perbedaan budaya, atau persepsi ketidakadilan dalam pembagian manfaat. -
Disintegrasi sosial di awal kedatangan
Transmigran harus beradaptasi dengan norma dan sistem sosial lokal. -
Ketergantungan pada bantuan pemerintah
Pada fase awal, beberapa transmigran bergantung pada bantuan sembako, peralatan, dan fasilitas lain.
3. Dampak Ekonomi Transmigrasi
a. Dampak Positif
-
Pembukaan lahan pertanian baru
Transmigrasi mendorong perluasan komoditas pangan, perkebunan, dan peternakan. -
Pertumbuhan ekonomi daerah terpencil
Aktivitas pertanian, perdagangan, dan jasa meningkat di lokasi transmigrasi. -
Penciptaan lapangan kerja
Baik bagi transmigran maupun penduduk lokal (konstruksi, jasa, transportasi). -
Munculnya pusat ekonomi baru
Contoh: Kawasan transmigrasi yang berkembang menjadi kota mandiri (Metro di Lampung, Konawe, Mamuju). -
Diversifikasi ekonomi rumah tangga
Selain bertani, muncul usaha kecil seperti warung, bengkel, dan UMKM.
b. Dampak Negatif
-
Biaya pembangunan yang besar
Infrastruktur, pembukaan lahan, dan modal awal membutuhkan investasi tinggi. -
Ketidakberhasilan ekonomi pada tanah marjinal
Beberapa lokasi memiliki kualitas tanah buruk (gambut, podsolik merah kuning), sehingga produktivitas rendah. -
Ketimpangan antara transmigran dan penduduk lokal
Kadang transmigran lebih cepat berkembang karena akses pelatihan dan modal.
4. Dampak Budaya Transmigrasi
a. Dampak Positif
-
Akulturasi budaya
Terjadi percampuran budaya seperti bahasa, makanan, kesenian, dan adat lokal. -
Peningkatan toleransi dan interaksi antar-etnis
Transmigrasi menciptakan masyarakat multikultural dengan nilai gotong royong. -
Pemeliharaan nilai kerja keras
Transmigran dikenal memiliki etos kerja tinggi sehingga mempengaruhi pola kerja masyarakat lokal.
b. Dampak Negatif
-
Potensi pergeseran budaya lokal
Bahasa lokal, ritual, dan adat bisa tergerus oleh budaya pendatang. -
Dominasi budaya tertentu
Terjadi jika jumlah transmigran lebih besar daripada penduduk lokal. -
Ketegangan antar etnis
Kasus konflik sosial di Sambas, Sampit, dan Lampung berkaitan dengan gesekan budaya dan ekonomi.
5. Dampak Lingkungan Transmigrasi
a. Dampak Positif
-
Pembukaan kawasan terencana
Pemerintah melakukan tata ruang permukiman dengan pola blok, sehingga lebih tertata dibanding permukiman spontan. -
Pembangunan infrastruktur hijau
Beberapa kawasan menerapkan konservasi seperti jalur hijau, sumur resapan, dan pola permukiman permanen.
b. Dampak Negatif
-
Deforestasi dan degradasi hutan
Pembukaan lahan transmigrasi menyebabkan hilangnya tutupan hutan di banyak wilayah (Sumatra, Kalimantan). -
Gangguan habitat satwa
Pembukaan kawasan baru dapat mengganggu ekosistem lokal (orangutan, harimau, gajah). -
Erosi dan degradasi tanah
Teknik pertanian yang tidak sesuai (tebang-bakar, tanpa terasering) mempercepat kerusakan tanah. -
Masalah keberlanjutan lahan gambut
Banyak kawasan transmigrasi ditempatkan di lahan gambut yang rentan kebakaran dan subsiden.
6. Contoh Kasus Transmigrasi di Indonesia
-
Metro – Lampung: Kawasan transmigrasi sukses menjadi kota mandiri.
-
Kawasan Transmigrasi Riau & Kalimantan: Banyak lahan gambut yang tidak produktif.
-
Sampit dan Sambas – Kalimantan: Konflik sosial akibat perbedaan budaya dan ekonomi.
-
Kabupaten Mesuji, Lampung: Perluasan perkebunan sawit berdampak pada pergeseran akses lahan masyarakat lokal.
7. Penutup
Program transmigrasi merupakan kebijakan geografi manusia yang berdampak multidimensi. Keberhasilannya bergantung pada:
-
kesesuaian lahan,
-
kesiapan sosial budaya,
-
tata ruang permukiman,
-
partisipasi masyarakat lokal,
-
serta keberlanjutan lingkungan.
Pendekatan people-centered development dan perencanaan berbasis wilayah menjadi kunci agar transmigrasi tidak hanya memeratakan penduduk, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
-
PERTEMUAN 6: ANALISIS SPASIAL TRANSMIGRASI
1. Konsep Dasar Analisis Spasial dalam Studi Transmigrasi
Analisis spasial adalah metode untuk mengkaji fenomena berdasarkan lokasi, keterkaitan ruang, dan pola persebaran.
Dalam kajian transmigrasi, analisis spasial digunakan untuk memahami:-
Pola lokasi permukiman transmigrasi
-
Kesesuaian lahan
-
Perubahan penggunaan lahan
-
Dampak lingkungan dan sosial-ekonomi
-
Interaksi penduduk lokal–pendatang
-
Perkembangan wilayah baru (growth center)
Transmigrasi adalah fenomena yang spatially dependent: keberhasilannya sangat ditentukan oleh kondisi keruangan.
2. Aspek Spasial yang Dianalisis dalam Program Transmigrasi
a. Lokasi dan Pola Persebaran
Meliputi:
-
Sebaran kawasan transmigrasi (statik & dinamik)
-
Pola permukiman: linear, memusat, grid, dan cluster
-
Aksesibilitas terhadap jalan, pasar, dan fasilitas publik
-
Kedekatan dengan pusat pertumbuhan
Metode analisis:
-
Peta tematik persebaran
-
Kernel Density Estimation (KDE)
-
Analisis pola titik (Nearest Neighbor Index)
b. Kesesuaian Lahan (Land Suitability Analysis)
Faktor yang biasanya dipetakan:
-
Jenis tanah (PMK, aluvial, gambut, ultisol)
-
Topografi (kemiringan)
-
Ketersediaan air
-
Drainase
-
Curah hujan dan iklim
-
Akses transportasi
Metode:
-
Overlay SIG
-
Weighted Overlay / Multi Criteria Decision Making (MCDM)
-
Analisis kesesuaian lahan FAO
c. Perubahan Penggunaan Lahan (Land Use/Land Cover Change)
Transmigrasi sering menyebabkan perubahan besar pada:
-
Hutan → Permukiman
-
Hutan → Pertanian/perkebunan
-
Semak → Sawah & kebun
Metode:
-
Citra satelit (Landsat, Sentinel)
-
NDVI & EVI
-
Change detection (post-classification comparison)
d. Dampak Lingkungan Spasial
Dapat dilihat melalui:
-
Deforestasi
-
Fragmentasi habitat
-
Penurunan tutupan vegetasi
-
Degradasi tanah
-
Kebakaran lahan gambut (di Kalimantan/Sumatra)
Metode:
-
Analisis hotspot (MODIS/VIIRS)
-
Fragmentation analysis (Fragstats)
-
Buffering terhadap kawasan konservasi
e. Dampak Sosial-Ekonomi Berbasis Ruang
Analisis meliputi:
-
Perubahan aksesibilitas ke pusat layanan
-
Perubahan harga tanah
-
Pertumbuhan pasar dan pusat ekonomi
-
Mobilitas penduduk
-
Pola interaksi sosial lokal–transmigran
Metode:
-
Analisis jaringan (network analysis)
-
Spatial autocorrelation (Moran’s I) terhadap indikator ekonomi
-
Pemetaan indeks kesejahteraan dan kemiskinan
-
PERTEMUAN 7: ANALISIS SPASIAL PERSEBARAN PERMUKIMAN
Pengertian
Analisis spasial persebaran permukiman adalah proses mengkaji lokasi, pola, dan hubungan keruangan antar permukiman pada suatu wilayah.
Tujuannya untuk memahami:-
bagaimana permukiman tersebar,
-
faktor yang memengaruhi persebarannya, dan
-
dampaknya terhadap struktur ruang wilayah.
Permukiman selalu dipengaruhi oleh kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan aksesibilitas.
2. Bentuk–Bentuk Pola Persebaran Permukiman
Secara umum terdapat tiga pola utama:
a. Pola Memusat (Clustered/Nucleated)
Ciri:
-
Rumah-rumah mengelompok pada satu pusat
-
Dekat sumber air, pasar, jalan utama
-
Dijumpai pada daerah subur atau pusat desa
Contoh: permukiman pedesaan di Pulau Jawa, pusat kota kecil.
b. Pola Memanjang (Linear)
Ciri:
-
Permukiman mengikuti koridor jalan, sungai, pantai
-
Muncul di wilayah pesisir, sepanjang jalan provinsi, atau tepi sungai
Contoh: permukiman sepanjang Jalan Lintas Sumatra.
c. Pola Mengelompok Acak (Dispersed/Scattered)
Ciri:
-
Jarak antar rumah berjauhan
-
Tersebar pada lahan luas
-
Muncul di daerah pertanian atau wilayah hutan yang baru dibuka
Contoh: banyak ditemukan pada kawasan transmigrasi baru atau daerah perkebunan.
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persebaran Permukiman
a. Faktor Fisik
-
Topografi
-
Dataran → pola mengelompok atau linear
-
Lereng/pegunungan → pola tersebar atau mengikuti kontur
-
-
Geologi & Jenis Tanah
Tanah subur → pemusatan permukiman;
Tanah marginal/gambut → persebaran menyebar. -
Ketersediaan Air
Dekat sungai/mata air → permukiman memusat. -
Iklim
Curah hujan dan suhu memengaruhi pilihan lokasi.
b. Faktor Aksesibilitas
-
Dekat jalan utama → pola linear
-
Dekat pusat ekonomi → pola memusat
-
Dekat fasilitas publik meningkatkan densitas permukiman
c. Faktor Ekonomi
-
Lahan pertanian produktif
-
Pusat perdagangan
-
Industri/pabrik
(Ketiganya menarik pemukim baru)
d. Faktor Sosial & Budaya
-
Pertalian kekerabatan → cenderung memusat
-
Budaya agraris → permukiman melebar di lahan terbuka
-
Urbanisasi → mendorong pertumbuhan permukiman padat
e. Faktor Kebijakan Pemerintah
-
Kawasan transmigrasi
-
Perumahan bersubsidi
-
Zona permukiman dalam RTRW
-
Pengembangan kota baru
4. Teknik Analisis Spasial Persebaran Permukiman
a. Pemetaan Pola Permukiman
Menggunakan:
-
SIG
-
Peta citra satelit
-
Peta topografi
-
Peta administrasi
Output:
-
Peta pola memusat/linear/tersebar
b. Analisis Kepadatan (Density Analysis)
Digunakan untuk melihat area dengan konsentrasi permukiman tinggi.
Metode:
-
Kernel Density
-
Point Density
-
Population Density Map
c. Analisis Pola Titik (Point Pattern Analysis)
Untuk mengevaluasi apakah persebaran permukiman:
-
acak,
-
teratur, atau
-
mengelompok.
Metode:
-
Nearest Neighbor Index (NNI)
-
Ripley’s K-Function
d. Overlay Faktor Fisik
Menggabungkan peta:
-
kelerengan
-
jenis tanah
-
jarak ke sungai/jalan
-
penggunaan lahan
Tujuan:
melihat hubungan spasial antara kondisi fisik dan persebaran permukiman.e. Buffering
Untuk menganalisis:
-
radius pengaruh jalan
-
area aman dari sungai
-
akses terhadap fasilitas publik
f. Analisis Jaringan (Network Analysis)
Melihat keterhubungan permukiman dengan:
-
pasar
-
sekolah
-
puskesmas
-
pusat kota
5. Contoh Penerapan Analisis Spasial Persebaran Permukiman
1. Kawasan Transmigrasi
-
Pola awal: grid teratur
-
Lama kelamaan: menyebar mengikuti aktivitas ekonomi
-
Analisis menunjukkan perpindahan pola dari planned settlement ke organic settlement
2. Permukiman Pesisir
-
Cenderung linear mengikuti garis pantai
-
Dipengaruhi oleh aktivitas nelayan dan akses laut
3. Perkotaan
-
Permukiman padat dan memusat dekat pusat kota
-
Menurun kepadatannya ke pinggiran (urban sprawl)
-
Analisis density dapat memetakan zona inti–transisi–suburb
4. Permukiman Pegunungan
-
Pola tersebar mengikuti kontur
-
Jarak rumah jauh karena kontur curam
6. Indikator Evaluasi Spasial Permukiman
Untuk menilai kualitas persebaran permukiman digunakan beberapa indikator:
1. Kesesuaian Lokasi
-
Jarak dari sungai (≥100 m)
-
Jarak dari lereng curam (>25%)
-
Jarak dari industri berpolusi
2. Aksesibilitas
-
Jarak ke jalan utama (<1 km ideal)
-
Jarak ke sekolah/puskesmas/pasar
3. Kepadatan
-
Kepadatan ideal di desa: 50–200 jiwa/ha
-
Kepadatan ideal kota: 400–800 jiwa/ha (zoning)
4. Tata Ruang
-
Sesuai RTRW
-
Tidak masuk kawasan lindung atau sempadan sungai
5. Lingkungan
-
Risiko bencana rendah
-
Sanitasi layak
-
Ruang terbuka memadai
7. Penutup
Analisis spasial persebaran permukiman sangat penting untuk:
-
perencanaan wilayah,
-
identifikasi kebutuhan infrastruktur,
-
evaluasi keberlanjutan, dan
-
pengendalian penggunaan lahan.
SIG dan citra satelit menjadi alat utama untuk mengidentifikasi pola, faktor pengendali, dan dinamika permukiman.
-
PERTEMUAN 8: UJIAN TENGAH SEMESTER
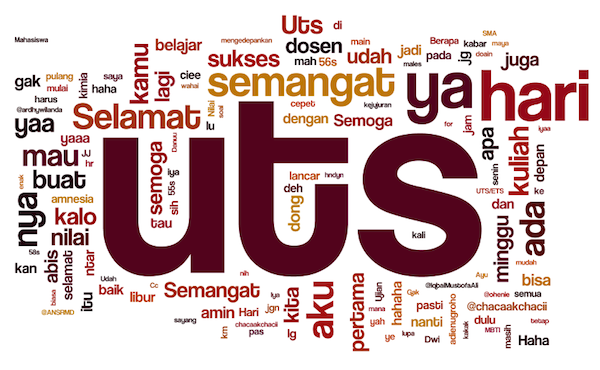
PERTEMUAN 9: IDENTIFIKASI POLA SEBARAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI
PERTEMUAN 10: KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN TRANSMIGRASI
PERTEMUAN 11: MODEL PERMUKIMAN BERKELANJUTAN BERBASIS GEOSPASIAL
Pengantar
Permukiman berkelanjutan adalah permukiman yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.
Model berbasis geospasial memanfaatkan data lokasi, citra satelit, dan analisis ruang untuk:-
Menentukan lokasi yang sesuai
-
Mengelola pertumbuhan permukiman
-
Meminimalkan dampak lingkungan
-
Meningkatkan kualitas hidup dan akses pelayanan
-
Mengukur keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologis
2. Kerangka Konseptual Permukiman Berkelanjutan
Permukiman berkelanjutan didasarkan pada tiga pilar:
A. Ekologis
-
Kualitas lingkungan baik (air, tanah, udara)
-
Penggunaan lahan ramah lingkungan
-
Risiko bencana rendah
-
Ketersediaan ruang terbuka hijau
B. Sosial
-
Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan transportasi
-
Keterlibatan masyarakat
-
Kenyamanan dan keselamatan permukiman
-
Pelestarian budaya lokal
C. Ekonomi
-
Kesempatan kerja
-
Infrastruktur ekonomi (pasar, transportasi)
-
Aksesibilitas terhadap pusat pertumbuhan
-
Efisiensi energi dan biaya hidup
3. Peran Geospasial dalam Pengembangan Permukiman Berkelanjutan
Teknologi geospasial digunakan untuk:
1. Penentuan Lokasi Permukiman
-
Analisis kesesuaian lahan (overlay tanah, kemiringan, air, risiko bencana)
-
Penilaian ruang terbangun vs ruang terbuka
-
Analisis aksesibilitas jalan dan fasilitas
2. Pemantauan Perubahan Lahan
-
Deteksi pertumbuhan permukiman
-
Urban sprawl
-
Deforestasi atau degradasi lingkungan
-
Pemadatan permukiman dari waktu ke waktu
3. Penilaian Risiko Bencana
-
Bahaya banjir
-
Longsor
-
Tsunami
-
Kebakaran hutan/lahan
Permukiman berkelanjutan harus berada pada zona aman.
4. Evaluasi Indikator Keberlanjutan
-
Kepadatan penduduk dan bangunan
-
Ruang hijau per kapita
-
Kualitas lingkungan
-
Akses terhadap fasilitas publik
5. Perencanaan Infrastruktur
-
Jaringan jalan
-
Transportasi publik
-
Air bersih & sanitasi
-
Energi terbarukan
4. Model Permukiman Berkelanjutan Berbasis Geospasial (6 Model Utama)
MODEL 1: Eco-Settlement Model
Ciri:
-
Mengutamakan konservasi tanah dan air
-
Tata ruang mengikuti kontur
-
Energi terbarukan (surya, biomassa)
-
Analisis geospasial: slope, curah hujan, tutupan vegetasi, drainage
Cocok untuk: daerah pedesaan konservatif, pegunungan, transmigrasi gambut/hutan.
MODEL 2: Compact Settlement Model
Ciri:
-
Permukiman padat tapi terkontrol
-
Penggunaan lahan efisien
-
Pusat aktivitas kompak (mixed-use)
-
Transportasi mudah dijangkau
Analisis geospasial:
densitas, network analysis, heatmap pembangunan.Cocok untuk: perkotaan, kawasan pengembangan kota baru.
MODEL 3: Transit Oriented Settlement (TOS)
Ciri:
-
Mengurangi ketergantungan kendaraan pribadi
-
Permukiman tumbuh di sekitar jalur transportasi
-
Jarak tempuh ke fasilitas publik pendek
Geospasial: buffering 400–800 m dari halte/jalur transportasi.
Cocok untuk: wilayah peri-urban, kota besar.
MODEL 4: Resilient Settlement Model
Ciri:
-
Berorientasi pada mitigasi bencana
-
Struktur rumah anti-bencana
-
Zonasi ketat pada kawasan rawan
Analisis geospasial:
-
peta risiko banjir/longsor
-
buffering sungai
-
model elevasi (DEM)
-
risk mapping
Cocok untuk: daerah rawan banjir, gempa, pesisir.
MODEL 5: Green Network-Based Settlement
Ciri:
-
Mengintegrasikan green belt, RTH, koridor ekologis
-
Ruang terbuka sebagai “tulang punggung” permukiman
-
Mengurangi urban heat island
Analisis geospasial: green space index, NDVI, landscape fragmentation.
Cocok untuk: kawasan urban dan suburban.
MODEL 6: Community-Based Spatial Settlement Model
Ciri:
-
Partisipasi masyarakat dominan
-
Pola ruang mengikuti budaya lokal
-
Pengelolaan ruang berbasis kearifan lokal
-
Mengutamakan keberlanjutan sosial
Geospasial: pemetaan partisipatif (PPGIS), overlay budaya, pemetaan sosial-ekologi.
Cocok untuk: desa adat, transmigrasi yang bersinggungan dengan masyarakat lokal.
5. Metode Geospasial dalam Penyusunan Model Permukiman Berkelanjutan
A. Analisis Kesesuaian Lahan (Weighted Overlay)
Variabel:
-
kemiringan
-
jenis tanah
-
jarak dari sungai
-
risiko bencana
-
akses jalan
-
ketersediaan lahan
B. Analisis Jaringan (Network Analysis)
Untuk:
-
aksesibilitas
-
optimasi rute
-
radius pelayanan fasilitas publik
C. Analisis Kepadatan (Density & Heatmap)
Untuk:
-
identifikasi permukiman padat
-
menentukan titik layanan baru
D. Land Use Change Detection
Untuk memantau:
-
pertumbuhan permukiman
-
konversi lahan hutan
E. Pemodelan Spasial (Spatial Modeling)
Untuk memprediksi:
-
arah pertumbuhan permukiman
-
risiko lingkungan masa depan
-
kebutuhan ruang dan fasilitas
6. Indikator Permukiman Berkelanjutan Berbasis Geospasial
A. Ekologis
-
RTH minimal 30%
-
Tingkat fragmentasi rendah
-
Kualitas air terpantau
-
NDVI stabil/meningkat
-
Risiko bencana rendah
B. Sosial
-
Akses fasilitas publik < 1 km
-
Kepadatan ideal (tidak terlalu padat/menyebar)
-
Partisipasi masyarakat tinggi
C. Ekonomi
-
Dekat pusat ekonomi (< 5 km)
-
Transportasi publik memadai
-
Diversifikasi lapangan usaha
7. Contoh Aplikasi dalam Konteks Indonesia
1. Permukiman Transmigrasi di Lampung & Sulawesi
-
Pola grid → mudah dianalisis
-
Cocok diterapkan Eco-Settlement + Resilient Settlement
2. Kota Baru Mandiri (BSD, Kota Baru Parahyangan)
-
Menggunakan geospasial untuk compact settlement dan green network
3. Permukiman Pesisir (Jakarta Utara, Semarang)
-
Diperlukan Resilient + Transit-Oriented Settlement
4. Desa Adat Bali
-
Cocok untuk community-based model
-
PERTEMUAN 12: MENGANALISIS KEBIJAKAN TRANSMIGRASI
PERTEMUAN 13: PENGAMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI
PERTEMUAN 14: RANCANGAN PENGEMBANGAN WILAYAH
1. Pendahuluan
Pengembangan wilayah transmigrasi bertujuan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru, pemerataan penduduk, serta peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan permukiman beserta sarana dan prasarana. Perencanaan wilayah transmigrasi saat ini tidak hanya fokus pada penempatan penduduk, tetapi juga menekankan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan ekologi.
2. Prinsip Utama Pengembangan Wilayah Transmigrasi
-
Berbasis Potensi Wilayah (Resource-Based Planning)
Mengembangkan sektor unggulan berbasis potensi lokal (pertanian, perkebunan, kelautan, agroforestry). -
Integrasi Ruang
Menghubungkan kawasan transmigrasi dengan pusat pertumbuhan regional (kota kabupaten/kota terdekat). -
Pembangunan Berkelanjutan
Memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, konservasi wilayah, dan mitigasi bencana. -
Inklusivitas Sosial-Budaya
Mendorong integrasi antara transmigran dan penduduk lokal tanpa menghilangkan identitas budaya masing-masing. -
Konektivitas dan Aksesibilitas
Prioritas pada pembangunan jalan, pasar, dan akses layanan publik.
3. Komponen Rancangan Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Komponen ini dapat menjadi kerangka kuliah.
A. Analisis Potensi dan Masalah Wilayah
-
Faktor fisik: topografi, tanah, iklim, risiko bencana.
-
Faktor sosial: struktur penduduk, pola permukiman lokal, potensi konflik, modal sosial.
-
Faktor ekonomi: komoditas unggulan, pasar, infrastruktur ekonomi.
-
Faktor lingkungan: kawasan lindung, hutan, alih fungsi lahan, batas ekologi.
B. Penataan Ruang Kawasan Transmigrasi (Spatial Planning)
-
Zonasi permukiman
-
Permukiman inti
-
Permukiman usaha
-
Ruang terbuka hijau
-
Kawasan budidaya
-
-
Zonasi kegiatan ekonomi
-
Pertanian dan perkebunan
-
Industri pengolahan
-
Perikanan/kelautan
-
Pariwisata berbasis alam dan budaya
-
-
Penyusunan jaringan infrastruktur
-
Jalan lingkungan & penghubung
-
Irigasi
-
Listrik & energi
-
Air bersih
-
Telekomunikasi
-
-
Analisis tata guna lahan berbasis SIG
-
Overlay peta penggunaan lahan, kemiringan lereng, curah hujan, dan risiko bencana
-
Penentuan suitability area untuk permukiman dan budidaya
-
C. Pengembangan Ekonomi Kawasan Transmigrasi
-
Pengembangan komoditas unggulan (agropolitan/agroestate)
-
Penguatan rantai nilai (value chain)
-
Pembangunan sentra usaha mandiri
-
Kemitraan dengan perusahaan (CSR, plasma-inti)
-
Diversifikasi ekonomi (UMKM, wisata, jasa)
D. Pengembangan Sosial dan Budaya
-
Integrasi sosial antara transmigran dan penduduk lokal
-
Forum komunikasi
-
Program budaya bersama
-
Konflik resolution mechanism
-
-
Penyediaan layanan dasar
-
Pendidikan
-
Kesehatan
-
Keagamaan
-
Administrasi kependudukan
-
-
Penguatan kelembagaan lokal
-
Desa/kelurahan
-
Gapoktan
-
Koperasi
-
E. Pengelolaan Lingkungan dan Mitigasi Bencana
-
Konservasi hutan dan sempadan sungai
-
Rehabilitasi lahan kritis & agroforestry
-
Pengelolaan limbah permukiman
-
Mitigasi bencana (banjir, longsor, karhutla)
-
Penerapan prinsip carrying capacity & ecological footprint
4. Tahapan Rancangan Pengembangan
Cocok untuk materi kuliah berbasis proyek (PBL).
Tahap 1. Identifikasi dan Delineasi Kawasan
-
Analisis spasial awal
-
Identifikasi batas kawasan calon transmigrasi
-
Inventarisasi potensi dan masalah
Tahap 2. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Transmigrasi (RTKT)
-
Pola ruang (budidaya & lindung)
-
Struktur ruang (infrastruktur utama)
-
Peta blok permukiman
-
Peta sistem usaha tani
Tahap 3. Desain Permukiman dan Usaha
-
Site plan permukiman
-
Pembagian lahan pekarangan dan lahan usaha
-
Penentuan model usaha (sawah, kebun, agroforestry)
Tahap 4. Pelaksanaan dan Fasilitasi
-
Penempatan transmigran
-
Pembangunan fasilitas publik
-
Pelatihan usaha
Tahap 5. Monitoring & Evaluasi Berkelanjutan
-
Evaluasi kesejahteraan
-
Evaluasi keberlanjutan ekologi
-
Penyesuaian rencana
5. Instrumen Geospasial untuk Pengembangan Wilayah Transmigrasi
-
SIG (GIS)
-
Pemetaan kesesuaian lahan
-
Pemetaan risiko bencana
-
Analisis aksesibilitas (network analysis)
-
-
Penginderaan Jauh
-
Identifikasi tutupan lahan
-
Monitoring perubahan hutan
-
Estimasi potensi air & deforestasi
-
-
Model Spasial
-
Land suitability model
-
Multi-criteria decision analysis (MCDA)
-
Spatial growth model
-
6. Model Pengembangan Wilayah Transmigrasi yang Relevan
-
Agropolitan Model
Menekankan pada pusat pertanian modern sebagai penggerak ekonomi. -
Rural Growth Center Model
Mengembangkan desa inti sebagai pusat layanan. -
Sustainable Settlement Model
Mengintegrasikan sosial, ekonomi, dan lingkungan. -
Cluster-Based Development Model
Kelompok permukiman terhubung sebagai satu sistem jaringan.
-
PERTEMUAN 15: MENYUSUN PORTOFOLIO
PERTMUAN 16: UJIAN AKHIR SEMESTER

